teologi 11
By bodohx.blogspot.com at Januari 19, 2024
teologi 11
Hubungan Kristen-Islam di negara kita menjadi salah satu studi
yang paling menarik untuk dicermati. studi atasnya semakin bergerak
menuju kesadaran bahwa relasi Kristen-Islam dalam sejarahnya tidak
pernah murni sebagai studi teologis. studi nya pun menjadi studi lintas
bidang dan lintas ilmu. Rupanya banyak faktor yang turut membentuk
dan mengkondisikan bangunan relasi itu. Apalagi sangat sulit menjumpai
sebuah agama tanpa terkait dengan kepentingan kelembagaan, kekuasaan,
dan interests tertentu, betapa pun tingginya nilai sosial yang dikandung oleh
kepentingan tersebut. Di negara kita , fenomena ini sangat mudah dijumpai.
Sederet faktor kemudian dicatat dan dianalisis. Selain untuk kepentingan
pengembangan studi ilmiah itu sendiri, hal ini juga menjadi kesadaran baru
umat beragama terkait kerentanan untuk gagal dalam usaha membangun
dialog dan memelihara kerukunan hidup bersama.
Di negara kita , relasi Kristen-Islam telah mengalami pasang-
surut seturut dengan sejarah perjumpaan keduanya. Banyak studi telah
memperjelas sejarah relasi yang problematis di antara keduanya . Seperti dicatat di atas, setiap studi atas relasi
Kristen-Islam semakin bergerak ke arah studi yang bersifat lintas ilmu.
Kesadaran ini tentu saja menunjukkan perkembangan yang baik. Justru
karena itu, setiap studi lintas agama diharapkan dapat menyentuh akar
persoalan (fundamental ideas), mengapa semakin rumit dan kompleks
relasi agama-agama di negara kita . Apalagi, dalam konteks masyarakat yang
keberagamaannya bersifat heterogen (majemuk, plural), persoalan hidup
bersama tentu cukup menggelisahkan. Hal ini sering tidak disadari bahwa
antara wilayah “normativitas” dan “historisitas” hidup keberagamaan sering
campur aduk, overlapped, yang perlu diklarifi kasi secara akademis untuk
menghindarkan dari praktik keberagamaan yang patologis ,
Salah satu studi yang menyadari studinya sebagai “studi lintas
ilmu” yaitu apa yang ditulis oleh Julianus Mojau. Tulisan Mojau yang
berjudul Meniadakan atau Merangkul? merupakan studi teologi sosial
yang cukup mendalam. Studinya bermaksud memperlihatkan aneka
model/tipe respon dari teolog-teolog Kristen Protestan dan lembaga
(PGI) dalam mengatasi “identitas kolonial” Kristen Protestan negara kita
berhadapan dengan Islam (politik). Yang menarik ialah—di beberapa
tempat—sang penulis menyadari betul bahwa mendekati subjek studi
tentang Kristen Protestan dan pergulatannya dengan Islam (politik), bila
hanya murni teologis, tidak akan tiba pada apa masalah (fundamental
ideas) yang selama ini menjadi “titik tengkar” keduanya. Karena itu,
aspek sosiologis dan politis menjadi penting ditelisik untuk masuk ke
rimba gelap relasi yang patologis antara keduanya dalam sejarah negara kita
Teks-teks teologi sosial yang diselidiki secara kritis juga tidak
berangkat dari dan dalam ruang hampa. Ia merupakan hasil pergulatan
teologis dari dan dalam konteks sosial tertentu. Karenanya, Mojau secara
sadar menggunakan pendekatan kritik-ideologi (ideological-criticism
approach) dan kecurigaan hermeneutis (hermeneutics-suspicion) untuk
membongkar wacana-wacana ideologis di balik rumitnya relasi Kristen-
Islam di negara kita ,Tulisan Mojau jadinya relevan disebut
sebagai teologi sosial, yaitu berteologi di tengah realitas sosial yang
kompleks. Kompleks karena kait-kelindannya antara yang “sakral”
dan yang “profan” lewat cara berpikir, interpretasi, dan tafsiran orang
perorang dan kelompok perkelompok keagamaan, yang kemudian hendak
diberlakukan secara “paksa” kepada pihak lain. Mengatasinya diperlukan
cara berpikir kritis, tidak terjebak dalam sektarianisme konsep dan praktik,
dan mampu berjarak (neutral) pada perebutan posisi status quo, hingga
pentingnya mengedepankan sikap toleran dalam arti praktis maupun
ilmiah.
Tulisan Julianus Mojau awalnya yaitu disertasi pada program
Doctor of Theology dari South East Asia Graduate School of Theology
(SEAGST), tahun 2004. Disertasi ini menganalisis secara kritis teks-teks
teologis sosial Kristen Protestan untuk menggambarkan upaya gereja-
gereja Protestan di negara kita pada periode Orde Baru dalam mengatasi
dan keluar dari tantangan konteks, secara khusus hubungannya dengan
Islam (politik). Sayangnya, tulisan Mojau ini—seperti yang penulis akui
sendiri—baru diterbitkan untuk konsumsi pembaca umum setelah delapan
tahun tinggal sebagai karya akademik (hlm. 405). Soal relevansinya, tulisan
ini saya kira merupakan sebuah sumbangan penting, tidak hanya di tataran
praktik politik bagi pencarian format pemikiran dan aksi politik Kristen
berhadapan dengan konteks, namun secara akademik menghubungkannya
dengan beberapa karya yang telah dibuat pada periode sebelumnya terkait
relasi Kristen dengan konteks sosial-politik di negara kita (misalnya: Ngelow disebut “teolog sosial pluralis”). Setidaknya
sampai satu dasawarsa akhir era Orde Baru, kita mendapat informasi kaya
mengenai respon Kristen terhadap konteks sosialnya.
Yang menarik dicermati yaitu apa yang ditulis oleh Gerrit Singgih
dalam edisi revisi Dari Israel ke Asia (2012). Singgih mencatat bahwa Julianus
Mojau yaitu orang yang telah melakukan pemetaan terhadap teologi politik
Kristen Protestan di negara kita Penjelasan ini
menjadi penting saat ditempatkan dalam konteks perkembangan pemikiran
teologi kontekstual di negara kita . Salah satu peta yang diungkap oleh Singgih
dalam perjalanan teologi kontekstual Kristen di negara kita ke depan yaitu
mengembangkan pemikiran di bidang politik. Dua peta yang lain yaitu
postmodernitas dan globalisasi. Masih dalam catatan Singgih, ia menegaskan
ulang pentingnya arah pengembangan teologi politik ke depan dalam sebuah
dialog dengan Majalah Wara Duta, katanya: “Kontekstualisasi baru diartikan
ke budaya tradisional saja, belum ke arah sosial, yaitu pemulihan harkat dan
martabat manusia. Jadi ke depan tugas gereja-gereja yaitu mengarahkan
kontekstualisasi teologia ke konteks sosial” Konteks
sosial juga berarti konteks politik.
Mengapa catatan di atas demikian penting? Rupanya selama
ini diskursus politik secara umum atau politik Kristen secara khusus
sering luput dari percaturan pemikiran dan refl eksi Kristen. Akibatnya,
konteks sekitar tidak pernah ditanggapi secara kritis, selain membeo
pada keadaan atau bersikap memusuhi konteks. Pengalaman di masa lalu
telah membuktikan bagaimana orang-orang Kristen mengambil posisi pro
status quo dan jauh dari keresahan sekitar. Faktor penyebab lain yaitu
besarnya kecurigaan pada politik, yang asalnya merupakan akar warisan
kolonial yang belum sempat ditransformasi. Padahal, sebagaimana kita
tahu, politik Kristen yang sering tidak cerdas dan tidak santunlah yang
selama ini memelihara “identitas kolonial” Kristen dalam relasinya dengan
kebudayaan-kebudayaan dan agama-agama lain, khususnya Islam. Atau,
seperti yang dicatat secara kritis oleh Mojau bahwa optimisme teologi sosial
model modernisme/pembangunan justru yang memperparah kebuntuan
relasi Kristen-Islam, menguatkan ketidakadilan struktural di masyarakat,
meningkatkan citra sosial negatif terhadap Kristen dan menciptakan
“identitas neo-kolonial” Kristen (hlm. 22). Melampaui situasi di atas,
kita berharap bahwa percakapan tentang politik yang semakin luas dalam
diskursus teologi Kristen, secara kritis dan akademis-ilmiah, akan memberi
banyak kesempatan lahirnya pemikiran-pemikiran baru yang refl ektif dan
semakin toleran. Mojau sendiri bermaksud melangkah lebih jauh, bahwa
konteks realisme sosial masa kini di negara kita memerlukan sebuah model
teologi sosial yang melampaui (beyond) ketiga model teologi sosial yang
dianalisisnya dalam rentang 1970-1990-an (hlm. 23, 405). Upaya ini pada
akhirnya akan membebat dan menyembuhkan banyaknya luka budaya dan
religi yang selama ini ditebar oleh kekristenan yang bermental kolonial atau
neo-kolonial.
Hal penting lain yang disuguhkan oleh karya Mojau yaitu bahwa
karya ini mengisi mata rantai perkembangan teologi Kristen Protestan
selama masa Orde Baru. Penegasan ini bermanfaat untuk kita rangkaikan
dengan salah satu tulisan penting dari Alle G. Hoekema, Berpikir Dalam
Keseimbangan yang Dinamis (1997). Studi Hoekema yang meneliti
rentang waktu satu abad (1860-1960) pergulatan Kristen Protestan dengan
teologi nampak minus kesadaran akan konteks agama-agama (terutama
Islam). Memang Hoekema sedikit meluaskan pandangan melampaui
waktu penelitian disertasinya dengan mewawancarai Harun Hadiwijono.
Dan, menurut Hoekema, baru tahun 1970-an, tepatnya tahun 1973, saat
diterbitkannya karya Iman Kristen oleh Harun, sebagai penanda munculnya
usaha sistematisasi teologi kontekstual yang sadar akan konteks agama-
agama Mata rantai yang saya maksud
yaitu bahwa studi Mojau melanjutkan studi Hoekema dan mengisi fase
penting pergulatan Kristen dengan konteksnya di era Orde Baru (1970-1990-
an). Yang dilanjutkan Mojau dari studi Hoekema, menurut Gerrit Singgih,
yaitu bahwa dalam kurun waktu antara 1860-1960 ada dua hal yang tidak
nampak dalam kesadaran teologi Kristen, yaitu konteks agama-agama
(terutama Islam) dan konteks kemiskinan (Singgih, 2005: 406). Di sini,
Mojau mengisinya pada konteks yang pertama. Sehingga, apa yang selama
ini dikuatirkan seolah terjadi diskontinuitas antara prototheologie dengan
teologi-teologi setelahnya, tidak terjadi. Kalaupun Mojau sendiri mungkin
tidak menyadarinya (?), maka kita dapat mengatakan bahwa studi tentang
prototheologie yang Hoekema lakukan menjadi inspirasinya (?). Saya kira
itu juga mengapa Hoekema kemudian memberi kata sambutan bagi buku
Mojau ini (hlm. xv-xix).
Isi Buku dan Beberapa Catatan Kritis yang Bersahabat
Studi Julianus Mojau tentang teologi sosial Kristen secara sadar
menggunakan tipologi (modernis, liberatif, pluralis) sebagai “pembedaan
kategoris” yang hampir tak terhindarkan untuk subjek studi yang demikian
kompleks Di sana-sini ada pesimisme soal
penggunaan tipologi karena dianggap tidak akan dapat mendekati masalah
(subjek studi ) yang demikian kompleks, karena justru mereduksi dan
mengaburkan masalah yang ada. namun kita dapat memahami pilihan Mojau
sebagai sesuatu yang argumentasinya kuat. Penjelasannya yaitu bahwa
tipologi itu sama dengan analogi “kandang” (fi gura) dalam fi lsafat Paul
Ricoeur Dalam fi lsafatnya, Ricoeur juga mengatakan
bahwa membuat “batas” (kandang) merupakan kecenderungan manusia
yang tidak tahan dengan banyaknya kemungkinan dan ketidakpastian.
Realitas terlalu “kaya akan makna-makna” (surplus of meaning). Yang
penting disadari bahwa setiap tipologi atau “kandang” tidak pernah akan
mengungkap persis-tepat realitas yang kompleks (contingent). Setiap
tipologi atau kandang hanyalah “alat bantu” membatasi jagat pergulatan
dalam model-model studi sosial apa pun. Studi Mojau ini sekaligus mewakili
salah satu perspektif—dari banyaknya kemungkinan (appropriation)—
mendekati realitas yang terlampau kaya sehingga tidak dapat dimutlakkan.
Jika demikian, “teologi sosial” yang Mojau gunakan pun yaitu tipologi.
Ini semacam “alat bantu” memahami realitas relasi Kristen-Islam yang
kompleks. Mojau sendiri menyebutnya “model” sebagai pembedaan
kategoris dalam mengidentifi kasi dan cara menafsir tipe-tipe atau ciri khas
pemikiran teologi sosial yang dikembangkan di kalangan Kristen Protestan
negara kita selama 1970-1990-an. Catatan pentingnya bahwa setiap tipologi
(kandang) tidak dapat dimutlakkan dan selalu dimungkinkan untuk diganti
dengan tipologi (kandang) yang lain.
Setelah bagian Pendahuluan, uraian Mojau masuk ke model-model
teologi sosial. Di Bab 1 diuraikan pemikiran-pemikiran teologi sosial
yang dirumuskan sejajar dengan proyek modernisasi Orde Baru. Melalui
pemikiran tokoh-tokoh seperti O. Notohamidjojo, T.B. Simatupang, P.D.
Latuihamallo, S.A.E. Nababan, dan Eka Darmaputera, terbangunlah teologi
sosial modernisme. Selain kelima tokoh, diuraikan juga model teologi sosial
yang dikembangkan oleh PGI (hlm. 27-142). Uraian Bab 1 ini menarik
karena hipotesis yang dikembangkan oleh Mojau mengatakan bahwa teologi
sosial model modernisme-lah yang selama ini memperparah hubungan yang
buntu antara Kristen-Islam (hlm. 22-23). Model ini menjadi “titik tengkar”,
ketimbang “titik temu”, di antara keduanya. Model ini juga menguatkan
ketidakadilan struktural di masyarakat, meningkatkan citra sosial negatif
terhadap Kristen dan menciptakan “identitas neo-kolonial” Kristen. Stigma
sosial sebagai pendukung peradaban kolonial akhirnya menjadi identitas
yang melekat dalam diri kekristenan. Hipotesis Mojau mengatakan bahwa
model teologi sosial modernisme-lah yang hendak “dipatahkan” (Mojau:
“diterobos”) oleh dua model teologi sosial lainnya, yaitu liberatif dan
pluralis (hlm. 142). Akhirnya, Mojau mengusulkan sebuah teologi sosial
sintesis.
Saya ingin memberikan catatan lain atas pilihan Mojau pada kelima
tokoh yang disebut dalam hipotesisnya sebagai pemikiran teologi sosial
yang tidak mendukung hubungan baik Kristen-Islam. Malahan, pemikiran
mereka mendukung gerakan modernisasi Orde Baru yang berarti pro status
quo kekuasaan Orde Baru (hlm. 21). Dengan dekat pada kekuasaan yang
kala itu sedang tumbuh, kekristenan dapat membenarkan praktik-praktik
ketidakadilan yang dilakukan oleh rezim yang baru. Yang saya ingin
katakan bahwa, sikap pro status quo pada kekuasaan dan mengembangkan
pemikiran teologis yang tidak mendukung hubungan baik Kristen-Islam,
nampaknya sulit untuk dipertahankan jika maksudnya itu yaitu S.A.E.
Nababan dan Eka Darmaputera.
Berdasar penilaian Sumartana, Mojau mengatakan bahwa Nababan
memiliki watak sosial yang primordialistis—buktinya merestui pendirian
HKBP di Minahasa —yang mengkristal dalam bentuk fobia
terhadap Islam politik (hlm. 94-95). Atas seluruh uraian terhadap Nababan,
di satu sisi, kritik atas wacana yang dikembangkan Nababan sangat kuat
ditunjukkan oleh Mojau. Namun, di sisi lain, kita masih bisa bertanya,
mengapa uraian Mojau tidak menyebut kiprah Nababan dalam konteks
perseteruan dengan PT. Indo Rayon, yang di mata masyarakat sangat
menghisap alam dan berlaku tidak adil terhadap masyarakat. Saya berbeda
dengan Mojau, bahwa uraian kecil konfl ik Soeharto dan Nababan awal tahun
1990-an (hlm. 95), saya kira—saya bisa salah—belum terlalu jelas dan utuh
menggambarkan sosok lain Nababan, bukan sebagai pendukung status quo
rezim penguasa waktu itu, melainkan pelawan kekuasaan. Setidaknya kalau
bukan di tataran wacana (“teks” yang dikritik Mojau), kita melihat praktik
politis Nababan, sebagai anti penguasa yang lalim, melalui keberpihakannya
pada penderitaan rakyat di sekitar PT. Indo Rayon. Kalau benar demikian,
Nababan rasanya tidak pas disebut hidup “jauh dari jeritan pilu” rakyat
(hlm. 95). Justru ia yaitu penyambung lidah rakyat yang menderita.
Terhadap Eka Darmaputera, Mojau pun menunjukkan bahwa
Eka punya sikap fobia terhadap Islam politik (hlm. 118), yang membuat
pesan Kerajaan Allah mandul tanpa daya transformatif. Melihat teks-teks
yang ditelusuri secara kritis, penilaian Mojau ini mungkin ada benarnya,
namun kita tidak boleh lupa bahwa sikap fobia Eka, juga Nababan, dan
teolog lainnya, terhadap tampilan Islam politik (hlm. 14-15: “Islam
fundamentalis”?) yang formalistik dan skripturalistik yaitu merupakan
sikap umum yang mulai tumbuh dan semakin menguat di kalangan generasi
Islam akhir 1960-an dan awal 1970-an. “Kegagalan” kaum modernis Islam
dalam memperjuangkan Islam negara menjadi bahan refl eksi generasi baru
Islam (hingga ke generasi 1980 dan 1990-an) untuk mewacanakan jalan
baru Islam ,Gerakan pembaharuan pemikiran Islam
(neo-modernisme) yang dimotori oleh Nurcholish Madjid dan tumbuh
di era awal Orde Baru, selain sempat dicap tidak kritis, dituduh memberi
legitimasi teologis pada kekuasaan, namun telah memberikan dasar teologis
yang paling cerdas bagi umat Islam untuk memikirkan ulang politik Islam
sebagai politik kesantunan dan jauh dari mematok mutlak kekuasaan
sebagai tujuan satu-satunya menjadi Muslim. “Islam Yes, Partai Islam No”
yaitu simbol teologis bagi pembaharuan pemikiran dan aksi politik Islam
ke arah yang lebih substansial.
Kesan Mojau bahwa neo-modernisme Islam meng-exclude-kan Islam
politik (hlm. 297), menurut saya, tidak terbukti, karena upaya pembaharuan
teologi lebih sebagai gerakan moral-intelektual. Di samping itu, pembaharuan
teologi itu telah meretas juga lahirnya Islam kultural, sebuah praksis Islam,
yang salah satunya concern dengan isu-isu ketidakadilan (sosial-ekonomi).
Dalam beberapa bagian (misalnya hlm. 370), dialog yang dimaksud Mojau
antara Kristen-Islam soal ketidakadilan, mungkin bukan dengan Islam
politik melainkan Islam kultural. Studi Bahtiar Effendi, saya kira, juga
telah membuktikan bahwa wajah Islam politik tidak saja substansial namun
juga skriptural (Effendi, 1998). Pada wajah yang skriptural (hlm. 14-15:
“fundamentalis”), yang penuh dengan interest, sebagai dampak warisan
konfl ik Kristen-Islam masa lalu, dan bersifat ideologis-tertutup, rasanya
tidak ada satu orang Islam pun yang mendukungnya (Hasan, 2006: 221),
apalagi seorang Kristen seperti Nababan, Eka, dan para teolog lainnya.
Meminjam uraian Gerrit Singgih, ia mengatakan bahwa syariat
Islam saja bisa diterima orang Kristen jika kebenaran, keadilan, dan
kasih menjadi premis nilai. Tak kalah penting, dapatkah orang Kristen
di wilayah yang memperlakukan syariat Islam menjadi ketua RT, camat,
hingga presiden? Bila tidak, maka kita pun menolaknya Kesan ini juga dapat dirasakan dari uraian Mojau sendiri.
Katanya, kita perlu sikap kritis pada kemungkinan retorika Islam politik
yang sebetulnya jauh dari pro keadilan dan pembebasan (hlm. 393). Kritis
bahwa Islam politik hanya dapat diterima karena ekspresinya yang nir-
kekerasan (hlm. 413). namun , di sinilah optimisme Mojau, semua daya kritis
itu tidak boleh menghalangi upaya mencari “titik temu” Kristen dengan
Islam politik demi mengembangkan teologi sosial liberatif-transformatif
Masih terkait ini, kita dapat
mempertanyakan “sumber kearifan sikap mental sosial rekonsiliatif” yang
ditawarkan Mojau dari 2 Korintus 5:17-19 (hlm. 397). Saya cuma mau
mengatakan bahwa bisa jadi basis ini memang tidak relevan (?) dan dalam
konteks polemik teologis justru dapat menjadi ganjalan dengan kalangan
Islam politik. Menurut saya, titik tolak dari dialog bisa bersumber dari
nilai-nilai sekular (walaupun nilai-nilai sekular sering dasarnya juga dari
nilai-nilai agama), yang juga beberapa kali disebut oleh Mojau sebagai
nilai-nilai humanitas. Dalam pembicaraan di seputar komunitas basis, ini
dimasukkan dalam Basic Human Community (BHC), di mana orang diikat
dalam praksis sosial oleh nilai-nilai kemanusiaan.
Dalam perspektif baru, wajah Islam politik telah bergerak
meruwat diri hingga bermakna kultural dan substansial sebagai praksis
emansipatoris dan transformatif. Jauh meninggalkan wajah lama Islam
politik (Islamisme), yang ideologis dan tertutup, menjadi wajah Islam
politik baru (post-Islamisme) yang terbuka dan toleran (Bayat, 2011). Post-
Islamisme yang toleran, juga terbuka bagi kerjasama agama-agama dalam
semangat humanisme. Yang menarik yaitu bahwa arus perubahan format
Islam politik (Islamisme) ini dalam banyak hal tidak dikarenakan faktor
luar, antara lain tekanan demokratisasi dan penegakan HAM di Barat,
melainkan perubahan internal umat Islam sendiri di bidang politik untuk
menjadi kontekstual dengan nalar publik masyarakat modern ,Artinya, harapan Mojau agar kita tidak
perlu galau dan khawatir dengan Islam politik (hlm. 407), dibenarkan
dengan realitas demokratisasi internal di kalangan umat Islam sendiri
berupa praksis “mengnegara kita kan Islam” ,
Catatan lain bahwa, sebagai teologi yang berangkat dari konteks,
maka pemikiran teologis dan sikap politis Nababan dan Eka yaitu teologi
kontekstual. Dalam berteologi kontekstual, kita tidak hanya melakukan
konfrontasi atas konteks (misalnya: Orde Baru), namun tak jarang juga
bersikap konfi rmatif/afi rmatif. Saya tidak bermaksud mengatakan bahwa
sikap pro kekuasaan itu pasti benar, namun jangan lupa, berteologi bukan
hanya soal orang yang berteologi, ia juga soal konteks yang melahirkan
setiap pemikiran teologis. Selain kita kritis karena kita mengambil jarak dan
memotretnya dari masa kini, kita juga dapat mengerti pergulatan yang tidak
sederhana dari setiap pemikir dan pemikirannya. Kritik besar atas pemikiran
teologi seseorang juga seringkali muncul karena pendekatan yang digunakan.
Setahu saya—saya bisa salah—kritik ideologi (ideological-criticism-
approach) yang Mojau gunakan (hlm. 24-25), yang bersifat dekonstruktif,
sangat kurang memberi apresiasi seimbang atas konteks lahirnya sebuah
pemikiran. Apresiasi baru muncul saat wacana itu telah habis-habisan
dibongkar, itu pun dengan maksud menunjukkan lubang-lubangnya ,Saya juga merasa penilaian Mojau soal empat karakter teologi
sosial modernis sebagai “kabar angin dari langit”, “menguatkan kekuasaan
hegemoni Orde Baru”, “membunuh kesadaran kritis umat”, dan “sungguh-
sungguh menjadi pabrik opium bagi rakyat” (hlm. 140-141), sangatlah
berlebihan. Sebab ada banyak faktor internal dan eksternal yang lebih
strategis untuk menguatkan kekuasaan hegemoni rezim Orde Baru.
Mojau juga bisa tidak konsisten saat ia mengevaluasi pemikiran teks-
teks teologi sosial-politik yang dikembangkan oleh lima teolog model modernis
berhadapan dengan ideologi negara, Pancasila. Menurutnya, pemikiran
mereka jauh dari kritis dan hanya menguatkan kekuasaan rezim Orde Baru.
namun , dalam akhir seluruh uraian, kesan saya, Mojau merekomendasikan
arah hidup menggereja sintesis yang karakternya pluralis, transformatif,
dan rekonsiliatif, juga dalam kerangka kesadaran dan semangat kebangsaan
negara kita , yang juga bersifatkan ideologi negara pasca Orde Baru dan
pasca amandemen UUD 1945 (hlm. 403). Kita belum terlalu jelas dengan
uraian Mojau ini, apakah maksudnya bahwa format ideologi pasca Orde
Baru dan pasca amandemen itu berarti ideologi yang telah ditransformasi
(Mojau: “format baru”), sehingga OK-OK saja menjadi titik tolak teologi
sosial (lihat kesan itu di hlm. 402). Dalam postcriptum, Mojau memang tidak
menyarankan bahwa titik tolak teologi sosial pluralis-liberatif-emansipatif-
rekonsiliatif itu berdasar pada format ideologi Pancasila seperti zaman Orde
Baru. Hanya kesan saya, Mojau agak berhati-hati. Di satu sisi, ia sadar
bahwa selama ini ideologi Pancasila telah dipakai sebagai alat kekuasaan,
dan orang-orang Kristen telah turut menggores luka pada umat Islam dengan
sikapnya yang mendompleng kekuasaan (teologi sosial modernis). Di sisi
lain, ada harapan besar bahwa dialog dengan kalangan Islam politik tidak lagi
berbasis ideologis (teologi sosial liberatif dan pluralis), melainkan didasarkan
pada cara memandang mereka sebagai sesama manusia dalam Keluarga
Allah (hlm. 409-410). Kalau masalahnya terletak pada ideologi Pancasila,
agak aneh, bahwa apa yang ingin dilampaui bersama kalangan Islam politik
justru dikatakan “mereka (Islam politik–pen.) dapat menerima Pancasila”
sebagai artikulasi politik mereka (hlm. 411). Saya menduga, Mojau masih
sangat optimis dengan Pancasila (?). Kesan optimis Mojau ini nampak saat ia
mengatakan perlunya mengembangkan rasa kebangsaan kerakyatan, sebagai
rasa kebangsaan alternatif, yang dapat didialogkan dengan rasa kebangsaan
pihak Islam, yaitu pada nilai liberatif dan emansipatoris (hlm. 376, diulang
dalam postcriptum hlm. 412). Ia juga positif—disertai nada kritis: “sayang
sekali”—terhadap amandemen Batang Tubuh UUD 1945 demi negara kita
baru (hlm. 378). Apakah ini tidak berarti bahwa dua-duanya toh bisa jadi
titik tolak bagi pengembangan teologi sosial pluralis-liberatif-emanisipatoris-
rekonsiliatif. Dari pada terkesan tidak konsisten, katakan saja: titik tolak
humanisme, OK! (Mojau), titik tolak ideologis, juga OK! (Yewangoe) (hlm.
407-408). Dengan demikian, bukankah masalahnya toh berpulang pada praktik
ideologi yang sering bergerak jauh dari ideologi itu sendiri. Sehingga yang
terpenting yaitu memperbaiki ideologi dan praktiknya sekaligus supaya bisa
menjadi titik temu (bukan “titik tengkar”) antar seluruh komponen bangsa
untuk hidup adil, sejahtera, dan merdeka.
Simatupang pernah berkata: “The fi ve (Pancasila) are a wide enough
umbrella for everybody. No body has anything against them, people can
accept them, we can all live together under them” , Kalau benar demikian, bukankah Eka Darmaputera juga sudah
merumuskannya Saya masih
ingin mengutip uraian Banawiratma yang sekiranya penting dan menolong
memahami titik tolak berteologi sosial dari pendekatan ideologi yang
ditransformasi.1 Katanya:
Di era Orde Baru, Pancasila dimanipulasikan demi kepentingan
kekuasaan yang represif. Di era reformasi ditenggelamkan oleh globalisasi
neoliberalis (dibiarkan oleh negara centeng, negara makelar)… Sekarang
ini: bukan masalah indoktrinasi melalui kurikulum atau institusi mana pun,
melainkan masalah praktek: nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila
itu diperjuangkan oleh negara dan oleh semua warga negara. Bagi iman
Kristen = ikut dalam gerakan Kerajaan Allah yang diperjuangkan oleh
Yesus: kerajaan keadilan, cinta kasih, kebenaran, persaudaraan semua
orang. Bagi iman Kristen perwujudan nilai-nilai Pancasila merupakan
penghayatan hidup mengasihi Allah dan sesama. Siapa itu sesama? Lukas
10:25-37. Mengasihi sesama yaitu sesama manusia dari orang yang jatuh
ke tangan penyamun (ay. 36),
Dua titik tolak ini (humanisme dan ideologi), saya kira juga yang
Singgih tawarkan bagi sikap politik Kristen di negara kita sekarang, yang
disebutnya sebagai “jalan tengah”, yakni negara tidak berasal dari Allah
namun ada (exist), karena itu kita taat kepada negara, namun kedaulatan negara
berada di bawah kedaulatan Allah. “Jalan tengah” ini mencoba tidak jatuh
pada dua ekstrem, di satu sisi sikap memisahkan diri atau melawan negara,
di sisi lain sikap menganggap negara berasal dari Allah, tidak peduli bahwa
negara itu jahat dan sering anti kemanusiaan ,
Mojau diakhir studinya merekomendasikan jalan keluar eklesiologis
yang mendesak untuk mengatasi identitas kolonial Kristen Protestan
di negara kita (hlm. 403). Setahu saya, ada pemikiran eklesiologi Eka
Darmaputera—sayang tidak tercantum dalam uraian halaman 96-119,
dan di daftar pustaka—yang sangat diapresiasi positif oleh teman-teman
Katolik (Keuskupan Agung Semarang). Salah satunya yaitu kata-kata Eka
dalam Sinode Agung Gereja Katolik negara kita (SAGKI) tahun 2000, bahwa
gereja-gereja di negara kita menghadapi situasi krisis yang amat serius “ke
dalam tidak signifi kan dan ke luar tidak relevan”
Pemikiran Eka ini rasanya jauh dari apa yang disebut Mojau, “mandul tanpa
daya transformatif” (hlm. 110, 118). Sementara itu, kata-kata kritis Eka
di atas yaitu juga yang diinginkan Mojau bahwa studinya ini bertujuan
eklesial sebagai evaluasi diri (autokritik) menuju panggilan liberatif dan
rekonsiliatif (hlm. 23). Demikian pula, mendukung maksud di akhirnya studi
Mojau sendiri tentang pembaruan eklesiologi untuk mengatasi identitas
kolonial Kristen Protestan (hlm. 403). Atau, jangan-jangan kritik yang tidak
berimbang ini makin membenarkan apa yang Banawiratma sering sebut
dalam perkuliahannya bahwa Eka Darmaputera lebih mendapat tempat di
kalangan Katolik daripada di Protestan sendiri (?).
Berikut saya akan menjelaskan dua bab selanjutnya, saya memiliki argumen yang kuat sehingga
secara sambil lalu saya akan memberi catatan kritis. Dalam Bab 2, Mojau
memperlihatkan bagaimana pemikiran teologi sosial dirumuskan dalam
rangka solidaritas dan pembebasan terhadap mereka yang menjadi korban
pembangunan ideologis. Melalui enam teolog, antara lain J.L.Ch. Abineno,
Josef Widiatmadja, F. Ukur, E.G. Singgih, dan A.A. Yewangoe, tergambar
teologi sosial terhadap kaum miskin, dan Marianne Kattopo mengembangkan
teologi sosial terhadap masalah keadilan gender. Bersama dengan teks-
teks teologi sosial PGI tersusunlah teologi sosial liberatif. Dalam Bab 3,
Mojau paling jelas dalam uraiannya tentang pemikiran-pemikiran Kristen
tentang Islam. Melalui tokoh-tokoh, seperti: Victor Tanja, Th. Sumartana,
E.G. Singgih, Zakaria J. Ngelow, Ioanes Rakhmat, dan teks-teks resmi PGI,
tercerminlah teologi sosial pluralis.
Pilihan Mojau pada tokoh-tokoh teologi sosial pluralis sangat
menarik dicermati. Mojau mengatakan bahwa ada alasan yang membuatnya
harus memilah di antara sekian banyak teolog, yaitu disertasi dan karangan
teologisnya mencerminkan posisi pandangan dan perspektif teologi kristiani.
Jika tidak, maka dengan sengaja diabaikan (hlm. 283). Salah satu yang
sengaja diabaikan yaitu Djaka Soetapa, karena disertasinya cenderung
menjadi ilmu agama murni dan tidak memperlihatkan pandangan dan sikap
Djaka Soetapa terhadap hubungan Kristen-Islam , Saya
ingin menunjukkan perspektif lain melihat Djaka Soetapa—juga membaca
disertasinya—yang membuatnya layak dimasukkan dalam deretan teolog
pluralis (atau mungkin modernis karena menyinggung Pancasila?). Teologi
Djaka Soetapa dapat dicerna melalui beberapa tulisannya. Yang utama
yaitu disertasinya. Dalam disertasi ini, Djaka memberi evaluasi kritis soal
pemaknaan sempit ummah sebagai din wa dawlah. Studi Djaka bermaksud
menemukan warna lain dalam teologi Islam tentang ummah yang dalam
konteks ke-“bhineka tunggal ika”-an negara kita dapat mengisi peran kreatif,
positif, dan konstruktif melalui transformasi konsep ummah eksklusif
menjadi “ummah negara kita ” inklusif.
Bagi Djaka Soetapa, konteks menentukan. Ummah yang semula
eksklusif diperluas dalam perjumpaan Islam dengan konteks kenegara kita an
yang majemuk. Pancasila yaitu pengikatnya. Di mana Islam menjadi
sumber etika dan moral bagi hidup sosial-politik. Islam menjadi sumber
nilai dan moral bagi kemanusiaan dan kenegara kita an. Potensi ini ada pada
sikap toleran Islam terhadap “pandangan dunia primal” penduduk setempat.
Katanya, usaha-usaha pembaruan Islam (puritanisme atau modernisme)
nyatanya tidak menghilangkan jati diri Islam negara kita yang heterogen dan
toleran Menurut saya, Djaka sedang membayangkan
sebuah “Islam sinkretik?”—seperti yang Sumartana pikirkan—yaitu Islam
toleran yang membangun harmoni dengan menerima unsur-unsur lokal,
berdialog dengan unsur keragaman lain dan memperluas medan dialog
melampaui konsep dan teologi din wa dawlah (negara Islam).4
Masih menurut Djaka Soetapa, ada 7 (tujuh) sumbangan
(“kejeniusan”) Islam bagi kenegara kita an , yaitu:
ummah wasat (umat penengah); umat teladan; gotong royong dan etika
sosial; Islam sebagai sikap pasrah, menjadi hamba Allah, dan mengabdi
pada sesama; pengakuan terhadap ummah “yang lain”; toleransi beragama
dan anti fanatisme agama; dan jihad sebagai kesukaan bekerja keras.
Pemikiran Djaka Soetapa ini sangat afi rmatif (lawan konfrontatif) terhadap
potensi Islam sebagai agama mayoritas. Djaka melampaui paradigma lama
misi Kristen yang konfrontatif-ideologis, yang berarti mengecilkan potensi
Islam. Untuk “jenius” Islam yang kelima (pengakuan Islam terhadap umat
lainnya), Djaka Soetapa menantang teologi Kristen untuk memikirkan
ulang tempat “yang lain” (Islam) dalam kerangka teologinya. Justru
teologi Kristen yang progresif-pluralis telah selesai dengan tempat agama-
agama lain, dan menjadikan dialog sebagai kesempatan diperkaya bahkan
dipertobatkan dari gambaran karikatur atas “yang lain” Dan karena Islam yaitu agama
yang paling bertetangga dengan Kristen, maka tempat Islam selesai dalam
rangka berteologi Kristen. Sejauh ini, penilaian Hoekema bahwa disertasi
Djaka Soetapa—walau menurutnya tidak mempunyai visi Kristen dan
mungkin ini yang diikuti oleh Mojau—merupakan “bukti adanya sikap baru
gereja (terhadap Islam)”, mengandung kebenaran Bila kita utuh melihat alur pemikiran dalam karangan-karangan
teologisnya, tidak hanya disertasinya (seperti yang dilakukan Mojau), maka
Djaka Soetapa layak dikategorikan sebagai teolog sosial pluralis, demikian
“pedialog” agama-agama ,
Catatan kritis lain yaitu apa yang Mojau kategorikan sendiri. Ia
memasukkan Th. Sumartana dalam tipologi “teolog sosial pluralis” . Tulisan Trisno Sutanto tentang “Perihal Kristen Liberal di
negara kita ” nampaknya luput dari perhatian Mojau
(dalam daftar pustaka Mojau tidak ada). Mungkin alasan paling masuk akal
yaitu bahwa tulisan Sutanto muncul setelah studi Mojau selesai. Karena studi
Mojau selesai tahun 2004 dan tulisan Sutanto muncul tahun 2004 juga. Hanya
saja bahwa, sub judul pembahasan Mojau atas Sumartana menyebut beberapa
kali “liberatif” dan bukan “pluralis” . Artinya,
bukankah ini malah mendukung apa yang ditulis Sutanto bahwa Sumartana
yaitu teolog Kristen liberal. Atau, dua-duanya bisa benar buat Sumartana (?):
teolog sosial liberal (Sutanto) dan teolog sosial pluralis (Mojau).
Sekarang saya masuk dan ingin memberi catatan dari uraian Mojau
di Bab 4, “Retrospeksi dan Prospek Teologi Sosial Pasca Orde Baru”. Mojau
mengatakan dua kali di halaman 400 bahwa oleh “kebesaran hati pihak umat
Kristen di sana (di Halmahera–pen.) untuk mau berdamai” maka perdamaian
terwujud dan ini yaitu contoh menggereja rekonsiliatif. Memang Mojau
menyebut peran pemerintah, lembaga adat, dan LSM dalam proses rekonsiliasi,
namun ada pertanyaan mendasar: di mana tempat saudara-saudara Muslim
dalam proses penyelesaian konfl ik ini? Apalagi, teologi sosial, yang juga
menyentuh teologi agama-agama, ingin merefl eksikan “bagaimana tempat
agama-agama dalam kerangka wawasan agama Kristiani” Jangan-jangan solusi konfl ik yaitu solusi satu pihak. Menurut saya,
sebagai studi yang fokus pada teks-teks atau wacana teologi sosial, sudah
tidak seharusnya umat Islam Halmahera tidak disebut dan seolah di-exclude-
kan. Padahal upaya membangun “teologi politik perangkulan” (theology of
embracing-politics) dan tidak meng-exclude-kan siapa pun (termasuk Islam
politik) menjadi benang merah dalam studi Mojau ,
Saya juga beroleh kesan—saya bisa salah—bahwa akhirnya
penyelesaian konfl ik menggunakan pendekatan lama, win-win solution.
Di sini kita dapat mempertimbangkan ide Henri Nouwen dalam bukunya
Yang Terluka yang Menyembuhkan (Nouwen, 1988). Gerrit Singgih, saya
kira salah satu teolog yang mengambil inspirasi Nouwen lalu menerapkan
pemahaman penyembuh yang terluka ini pada proses kesembuhan
rekonsiliasi, yang hanya bisa terjadi di antara dua pihak yang sama-
sama kalah atau sama-sama korban, dan bukan yang sama-sama menang
Aspek rekonsiliatif ini mengingatkan para pegiat
resolusi konfl ik –baik konfl ik etnis atau agama—untuk sadar bahwa
konteks kasus menderita karena kekerasan dan usulan penyelesaiannya
dengan win-win solution, ternyata solusi tersebut tidak mungkin bisa
dijalankan. Kutipan di atas sekaligus mau mengatakan bahwa kritik
Mojau terhadap teologi sosial pluralis sebagai kurang menekankan
aspek rekonsiliatif (hlm. 379) tidak terbukti pada Singgih (setidaknya
pada tulisannya kemudian dan disebut Mojau di halaman 414). Bahasan
dalam buku Nouwen juga memberi perspektif lain (dari kesan saya
terhadap Mojau), dan menolong untuk memotret konteks di negara kita ,
yang disadari berbeda dengan konteks Nouwen, bahwa kita semua –tidak
mengenal latar agama apa pun— sama-sama sedang menderita karena
polarisasi masyarakat, menjadi korban kekerasan dan teror yang dilakukan
oleh sesama bangsa.5 Orang-orang Kristen pengajur model teologi sosial
modernis yaitu korban karena sikap fobia terhadap Islam politik yang
beragendakan negara Islam, demikian kalangan Islam politik yaitu
korban karena sikap fobia terhadap bahaya kristenisasi ,
Mojau dalam Bab 4, saya kira sudah memberi sinyal bagi upaya
membangun titik temu Kristen-Islam atas dasar keprihatinan sosial
bersama (hlm. 395-396). Sinyal itu yaitu pentingnya membangun
komunitas-komunitas liberatif-transformatif lintas budaya dan agama
demi perjuangan hidup bersama yang damai dan adil. Hanya saja, menurut
saya, walaupun studi Mojau juga menyinggung pemikiran teologi sosial
lembaga seperti PGI dan lembaga di dalamnya, namun masih besar
ruang pembahasan diberikan kepada pemikiran tokoh-tokoh (15 tokoh,
Singgih disebut dua kali) dari mana teologi sosial itu muncul ,Mojau sendiri menyebut porsi singkat uraian tentang PGI
demikian: “Seperti halnya kedua model teologi sosial lain... saya akan
memeriksa secara singkat...” (hlm. 284, 145). Bagi saya, ini menguatkan
pandangan dalam kesimpulan studi saya—tesis magister teologi di Duta
Wacana: Teologi Progresif—bahwa pemikiran teologi Kristen Protestan
masih berkutat pada tokoh dan belum menjadi sebuah “gerakan sosial”
Lalu saya mengusulkan dalam studi saya bahwa
pembaruan teologi Kristen ke depan (saya secara sadar menggunakan
tipologi “teologi progresif”), yang berdaya bagi transformasi sosial,
haruslah berwujud “kerja kolektif”. “Kerja kolektif” yaitu gerakan
pembaruan teologi pasca “kerja individu”, bersama dengan “kerja-kerja
kolektif” dari komponen sekular dan umat beragama lain (lintas iman
dan lintas budaya) untuk mengatasi aneka patologi globalisasi melalui
mobilisasi religius. Kesadaran ini, menurut saya, punya nilai strategis
untuk menghubungkannya dengan apa yang terjadi di dalam internal umat
Islam. Ahmad Suaedy (aktivis The Wahid Institute) mengatakan bahwa
pasca Orde Baru, gerakan pembaharuan pemikiran dan sosial Islam
tampil sebagai “kerja kolektif” dalam lembaga-lembaga ilmiah atau LSM
intelektual ,Tulisan Budhy Munawar-Rachman
secara jelas mencatat pertumbuhan 11 (sebelas) lembaga pengarusutamaan
(mainstreaming) dan diseminasi Islam progresif-kontekstual di negara kita
. Fakta ini tentu menantang untuk gagasan
pembaruan Kristen diinstitusionalisasi menjadi “kerja-kerja kolektif”
dalam lembaga-lembaga pengarusutamaan (mainstreaming) gerakan
sosial liberatif-transformatif Kristen.6 Ini juga yang saya kira dicermati
oleh Hoekema, yang ia katakan dalam “Kata Sambutan” buku Mojau,
bahwa ke depan arah perkembangan teologi Kristen Protestan yaitu
dengan memberi perhatian pada “bengkel-bengkel” (“kerja kolektif”–
pen.), di mana aneka gagasan dan refl eksi teologis itu dipraktikkan
dalam dialog dengan umat lain dan di banyak tempat (Hoekema, “Kata
Sambutan”, dalam Mojau, 2012: xviii-xix).
Hal lain yang menurut saya perlu dicermati yaitu kritik Mojau
bahwa teologi sosial Kristen sepanjang Orde Baru tidak punya kerangka
metodologi yang jelas, terlalu menekankan isi teologi, abstrak, tidak
menolong orang-orang (umat, gereja) mengalami langsung situasi, sering
kali hanya membenarkan situasi yang mapan, dan akhirnya akan tinggal
retorika belaka (hlm. 381). Penilaian ini menurut saya tidak bisa tinggal
seperti ini tanpa penjelasan. Karena bisa diartikan semua pemikiran para
teolog yang dianalisisnya sama saja (hlm. 373). Sebab, anggapan bahwa
pengutamaan isi teologi hanya akan membenarkan kemapanan, menurut
saya yaitu prasangka Mojau. Karena, kita pun bisa mengatakan sebaliknya,
bahwa tekanan pada metode—sesuatu yang ditawarkan Mojau (hlm. 380-
381)—juga bisa menindas. Sejarah teologi Barat yang diterapkan pada
zaman kolonial rasanya contoh baik betapa teologi dan seluruh perangkat
metodologinya telah dipakai membenarkan kolonialisme . Saya setuju dengan Mojau bahwa
berteologi perlu metodologi. Itu juga yang ia kritisi pada warisan teologi
yang dimiliki para teolog (khususnya model modernis) yang mengontrol
bawah sadar mereka sehingga menghasilkan teks-teks yang kabur dari
keprihatinan konteks. namun jangan seolah ada dikotomi berlebihan—kesan
membaca halaman 381: “Hal ini penting sebab...”—karena baik isi dan
metode sama-sama penting bagi berteologi kontekstual. Yang tak kalah
penting bahwa, baik isi dan metode teologi, sama-sama tidak bebas kritik.
Penerapan dan relevansinya dalam ruang publik teologi akan ditentukan
oleh dialog publik dan keterbukaan pada kritik.
Berangkat dari uraian di atas, kritik Mojau bahwa teologi sosial
Kristen sepanjang Orde Baru tidak punya kerangka metodologi yang jelas
dan abstrak, menurut saya, tidak terlalu mengena jika maksudnya tertuju pada
pemikiran Gerrit Singgih, misalnya. Memang Mojau sudah menguraikan
salah satu kesadaran metodologis yang ada pada Singgih: “konfrontasi”
dan “konfi rmasi”. Mojau juga sudah memberi evaluasi kritis dan positif
bahwa Singgih yaitu pengecualian teolog, baik modernis dan liberatif,
yang punya metodologi jelas dalam berteologi (hlm. 203-204). saat
mengusulkan jalan keluar mengatasi kebuntuan hubungan Kristen-Islam
berupa langkah metodologis yang disebut “lingkaran hermeneutik” (hlm.
384), saya kira Mojau sejalan dengan Gerrit Singgih namun saya ingin memberi catatan lain, bahwa
kritik terhadap metodologi teologi sosial era Orde Baru (termasuk bila itu
Singgih [?]) datang karena Mojau tidak dapat membedakan antara isi wacana
teologi sosial (tataran diskursus pemikiran) dan praktik wacana. Menurut
saya, sebagai sebuah wacana, isi teologi bisa saja abstrak. namun isi tersebut
juga konkret karena berangkat dari pengalaman komunitas. Sementara itu,
praktik wacana sebagai konkretisasi isi wacana yaitu langkah berikut.
Setahu penulis, kesadaran metodologis Singgih banyak yang berangkat
dari pengalamannya yang konkret, antara lain sewaktu memimpin LPM
Duta Wacana (1987-1993) dan beberapa waktu sebagai pendeta jemaat
(beberapa tulisan Singgih berbicara tentang GPIB, GKJ, GKP). Ini yang
tidak dilihat Mojau dan mungkin yang Hoekema maksudkan dalam Kata
Sambutannya dengan menyebut “bengkel-bengkel” (hlm. xviii), yaitu
“tempat” di mana isi wacana (diskursus pemikiran) dan refl eksi teologis
hendak didaratkan, menjadi konkret (tidak abstrak), populis dan akhirnya
menolong umat dan gereja mengalami langsung situasi hidupnya. Hanya
saja, menurut saya, “bengkel-bengkel kerja” ini juga yaitu upaya lanjutan,
dan itulah yang mungkin Hoekema sarankan buat isi wacana teologi yang
digagas oleh Mojau (teologi sosial sintesis), untuk akhirnya konkret, tidak
abstrak, dan menolong umat dan gereja. Konkretnya isi sebuah wacana
teologi (termasuk teologi sosial sintesis) yaitu dengan institusionalisasi
gagasan dan penguatan lembaga-lembaga progresif-liberatif-transformatif
yang semakin lintas iman dan lintas budaya. Gerrit Singgih rasanya sudah
mencatatnya, antara lain, tugas sekolah teologi seperti “tukang bengkel”
yang mereparasi teologi umat atau gereja, sehingga umat atau gereja
kemudian berdaya dalam memerankan fungsi liberatifnya . Hanya saja kritik Mojau bisa ada benarnya karena Gerrit
Singgih memang baru menulis antologi, bukan karya teologi yang utuh.
Sehingga bukan asli dari pemikirannya sendiri
Mojau juga berpendapat bahwa: “Sejauh pengetahuan saya, selama
Orde Baru belum ada rekonsiliasi antara umat Islam dengan umat Kristen
di negara kita ” (hlm. 401). Bagi saya, maksud kalimat di atas belum terlalu
jelas. namun , kalau yang diharapkan yaitu rekonsiliasi yang sifatnya
formalisme-seremonial dan dikerjakan oleh negara (?), bukankah ini
justru kemunduran karena makin membenarkan relasi kooptatif yang
selama ini terjadi dalam sejarah dialog agama-agama semasa Orde
Baru dan menambah kebuntuan relasi Kristen-Islam. Selain itu, upaya
rekonsiliatif yang formalistik-seremonial dapat menutup apa yang telah
dicapai selama ini oleh gerakan-gerakan sosial yang seringkali bersifat
non-formal dan tidak pernah terencana, karena dihidupi dalam relasi
keseharian bertetangga. Menurut saya, rekonsiliasi itu sudah terjadi dan
terus berlangsung dalam gerakan-gerakan sosial non-institusional dan
institusional non-pemerintah. Selain itu, seperti harapan Mojau, bahwa
kebuntuan hubungan Kristen-Islam hanya dapat diterobos bila gereja-
gereja dan umat Kristen di negara kita mau mengambil inisiatif (hlm. 401),
juga sudah terjadi, walaupun sejauh mana itu diwujudkan masih perlu
dicermati. Saya ingin menunjukkan contoh inisiatif Kristen yang bersifat
institusional—halaman 401: Mojau mencontohkan tahun 1974 [?], lihat
juga contoh halaman 414—pada Sidang Raya XIII PGI di Palangkaraya,
Maret 2000, yang disebut sebagai “Sidang Pertobatan”.8 Dalam sidang ini
kita mendengar kata-kata permohonan maaf Sekretaris Umum dan utusan
Uniting Churches in the Netherlands, Dr. B. Plazier. Kata sambutan itu
yaitu juga suara gereja-gereja di negara kita , untuk memohon maaf pada:
sikap eksklusif yang memperlebar jurang antara Muslim dan Kristen;
sikap superior atas orang Islam negara kita yang diwariskan kepada gereja-
gereja di negara kita ; dan sikap menganggap diri orang Kristen tulen
dengan status teologi dan rohani yang lebih tinggi ,Jadi, sejauh pengamatan saya, secara formal kita sudah
mempunyai contoh-contoh inisiatif rekonsiliasi yang perlu dijadikan way
of life (cara hidup) dalam dialog kehidupan (non-formal), untuk meretas
teologi pertetanggaan bersama dengan umat Islam (termasuk Islam
politik). Dalam postcriptum, Mojau sudah memperlihatkan perkembangan
yang menggembirakan dengan munculnya tema-tema rekonsiliatif dalam
diskursus teologi sosial di negara kita paling akhir
Saya berbeda dengan kesimpulan akhir studi Mojau yang melihat
(hanya [?]) eklesiologi sebagai tema mendesak untuk mengatasi kebuntuan
hubungan Kristen-Islam di negara kita ,Studi
saya, Teologi Progresif, menunjukkan bahwa pembaharuan eklesiologi
tidak cukup. Secara utuh harus disebut bahwa pembaharuan hermeneutik,
teologi, eklesiologi, dan misiologi (inspirasi dari Gerrit Singgih) yaitu
sama-sama dan sejajar dikerjakan untuk pembaharuan praksis berteologi
Kristen “mengatasi identitas kolonial”, lalu terajut dengan konteks
negara kita . Uraian Singgih sendiri tentang orientasi baru hermeneutik,
teologi, eklesiologi, dan misiologi yang kontekstual sejajar dengan apa
yang dikatakannya dalam “Prakata” buku Bergereja, Berteologi, dan
Bermasyarakat, bahwa: “bergereja” (dan bukan hanya ke gereja) ini sejajar
dengan eklesiologi kontekstual, “berteologi” (dan bukan hanya secara pasif
mengulang-ulang warisan teologis yang diterima dari para pendahulu) ini
sejajar dengan teologi kontekstual, dan “bermasyarakat” (dan tidak hanya
memperhatikan soal-soal intern gerejawi saja) ini sejajar dengan misiologi
kontekstual ,
Terakhir, saya mencatat beberapa kesalahan teknis penulisan yang
tentu tidak akan mengurangi keseluruhan isinya. Di halaman 16 baris 6
dari atas, ada penulisan kata oleh dua kali. Di halaman 141 baris 19
dari atas, tertulis para kelima teolog, saya kira cukup ditulis para teolog
atau kelima teolog. Di halaman 187 baris 9 dari bawah, perlu ada tambahan
kata gereja, sehingga menjadi “pendeta salah satu gereja anggota PGI”. Di
halaman 326, c.k. 91, buku yang ditulis Gerrit Singgih tertulis judul, Iman
dan Reformasi dalam Era Reformasi di negara kita , seharusnya Iman dan
Politik dalam Era Reformasi di negara kita . Di halaman 370 baris 4 dari atas,
perlu ada tambahan kata belum, sehingga kalimatnya menjadi “penekanan
teologi sosial liberatif itu belum cukup mendapat tempat yang menonjol ...”.
Penutup
Saya harus mengakhiri tinjauan ini di sini, seraya menyadari bahwa
apa yang dilakukan ini yaitu “upaya coba-coba”, yang tidak bermaksud
mengurangi sumbangan besar dan relevansi penting yang diberikan oleh
studi mendalam Dr. Julianus Mojau bagi pengayaan khasanah berteologi
kontekstual di negara kita . Sebagai “upaya coba-coba” maka saya memastikan
akan ada kemungkinan lain untuk membaca dan meninjau karya Mojau ini
secara lebih baik dan mendalam. Dan sudah barang tentu memiliki dan
membaca langsung buku Meniadakan atau Merangkul? akan jauh lebih
enak dan mengasyikkan. Olehnya kita dibantu untuk menimbang-nimbang
dari mana dan mau ke mana (sangkan paran) arah berteologi kontekstual
kita ke depan. Dari membaca, dan terjadi pertemuan dua horison, kita
diharapkan arif menjadi umat beragama dalam konteks di mana kita ada.
Satu hal yang saya kira penting untuk selalu dipikirkan yaitu soal
tempat agama-agama lain dalam kerangka berteologi Kristen. Ini yaitu
kesadaran yang relatif baru. Banyak orang Kristen tidak mau tahu dengan
keberadaan agama-agama lain. Pergaulan tidak otomatis merupakan
“pengakuan” mengenai “tempat” (Islam, dll.) di dalam kerangka teologi
Kristen. Di sini, kita perlu mentransformasi “politik Kristen mayoritas”
yang ambigu: cenderung mendekat pada kekuasaan dan berarti pula
menolak untuk mengakui keberadaan diri yang minoritas. Kita perlu
mempertimbangkan tawaran untuk mengembangkan “politik Kristen
minoritas”, agar kita belajar ulang menerima keberadaan Kristen sebagai
minoritas yang mempunyai hak dan kewajiban sama dengan mereka yang
menjadi mayoritas . Dengan jalan inilah orang-
orang Kristen dapat kembali belajar bergaul dengan mengakui eksistensi
“yang lain” (the other). Pengakuan atas eksistensi “yang lain” merupakan
anugerah!

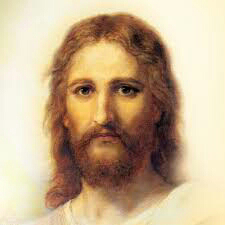



.jpg)






